Mencari Sekolah Rakyat
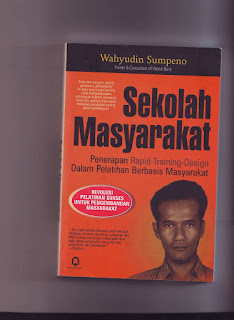
Judul Buku : Sekolah Masyarakat, Penerapan Rapid-Training Design Dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat
Penulis : Wahyudin Sumpeno
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Cetakan : Mei, 2009
Tebal : 329 Halaman
Peresensi : Matroni Muserang*
Sekolah merupakan tempat mengembangkan diri, bukan hanya intelektualitas saja, tapi juga ruang untuk menggali kreativitas serta bakat yang dimiliki generasi yang diagung-agungkan sebagai penerus bangsa. Saat ini banyak sekolah yang bersaing. Bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasti juga. Baik secara akademik maupun non akademik.
Semua masyarakat tahu perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Itulah yang membuat para orang tua berpikir, dimanakah anakanya akan disekolahkan? Apalagi sekarang ada sekolah yang menggunakan standar internasional. Sekolah yang sebenarnya adalah sekolah yang tidak mementingkan gengsi, namun yang harus dipentingkan adalah kemampuan siswa dalam semangat belajar untuk meraih kesuksesan di masa depan.
Kini dengan naiknya standarisasi yang diberikan pemerintah membuat para calon siswa sulit mendapatkan sekolah yang diinginkan, dan terkadang hanya hanya demi mewujudkann keinginan anak, orang tua berbuat pragmatis daripada etis. Cara-cara yang tidak semestinya ini dilakukan ini justeru memberikan kesempatan bagi golongan ekonomi ke atas, sehingga keluarga yang berekonomi rendah kesulitan mencari sekolah sebagai tempat mendidik anak-anaknya.
Tujuan adanya sekolah adalah menjadikan penerus bangsa maju dan berilmu, namun sayang, hal itu belum benar-benar terealisasikan, apalagi syarat-syarat yang diajukan pihak sekolah yang terkadang memberatkan calon siswa dan orang tua. Dalam hal peningkatan kualitas, standarisasi dan berbagai kebijakan yang ditawarkan sekolah tentu sangat baik, akan tetapi menjadi iranis ketika masyarakat (terutama keluarga miskin) justreru kesulitan mencari sekolah rakyat yang benar-benar sesuai dengan kondisi riil mereka.
Realitas saat ini sekolah telah dijadikan komoditas politik. Lalu bagaimana nasib sekolah pasca pilpres? Mungkin sekolah gratis merupakan terobosan yang sangat bagus. Namun terangkatnya program tersebut berbarengan dengan musim kampanye. Seolah-olah pemerintah memanfaatkan masa kampanye guna menarik simpati. Nanun di luar isu kampanye, program tersebut sangat positif. Sekolah gratis, manfaatnya sangat dirasakan masyarakat.
Dari beberapa indikator tersebut menandaskan ihwal sekolah kita selama ini masih menjadi lembaga yang elitis dan tidak berpijak pada konteks realitas kehidupan masyarakat. Dari aspek pengambilan kebijakan, layaknya UN dan BHP Wahyudin melihat sekolah menua kontroversi tapi pemegang kebijakan tidak mengacuhkan. Suara guru yang ada dipelosok seakan diangap sampah yang dibiarkan begitu saja. Padahal secara sosiologis dan antropologis mereka para guru dan praktisi sekolah tidak hanya sekedar mengetahui kondisi sekolah yang sebenarnya, tapi mereka juga merasakan dan mengalami bagaimana sesungguhnya kebijakan ketika digulirkan.
Bagi Wahyudin sebagai penulis buku ini elitisme kebijakan ini tidak terlepas dari ketidakberpihakan pemegang kebijakan pada kalangan lembaga sekolah yang ada di kelas bawah. Pemegang kebijakan lebih menghamba pada kepentingan golongan kaum kapitalis. Pertimbangan yang dipakai tidak berbasiskan pada konteks masyarakat secara umum, tapi lebih berbasiskan pada pada kalangan elit lembaga sekolah tertentu dan elit-elit kapitalis. Ketidakberpihakan kebijakan terhadap realitas tidak sepenuhnya disebabkan karena kekurangtahuan, tapi kesengajaan juga menjadi sifat yang selama ini seakan dominan.
Satu contoh adalah latar belakang munculnya BHP. BHP tidak semata-mata hadir begitu saja. Pasca-perjanjian LoI (letter of intens) 1999 yang mengharuskan pemerintah mengurangi subsidi terhadap pendidikan ternyata pemerintah kambali menyepakati agenda WTO (World Trade Organization) 2004 yang menjadikan sekolah sebagai sektor jasa, sektor yang kemudian dapat diperjualbelikan. Perjanjian itu membawa dampak yang sangat buruk bagi dunia sekolah dan anak didik kita. Penandatanganan perjanjian itu memunculkan kebijakan menswastanisasikan PTN (perguruan tinggi negeri) melalui pem-BHMN-an. Tidak heran apabila banyak kebijakan-kebijakan sekolah banyak yang menguntungkan kaum sepihak dan menindas kaum kebanyakan.
Sekolah yang dalam proses pengambilan kebijakan elitis juga akan melahirkan ragam pengangguran bagi mereka para kaum terdidik. Dalam kontek ini bahasa pengangguran berkonotasi pada mereka orang-orang yang tidak punya pekerjaan produktif yang bisa mencukupi hidupnya. Orang yang menganggur adalah orang yang sudah kehilangan pamor dalam mengikuti pola gerak kehidupan sehingga mereka harus tersisihkan. Pengangguran adalah tipologi orang yang tidak mempunyai jati diri alias tidak tahu potensi dirinya yang sebenarnya sehingga mereka harus berdiam diri. Realitas inilah yang sebenarnya dikhawatirkan Wahyudin.
Mandeknya pengembangan keilmuan menjadi masalah fundamental yang mengakibatkan siswa menjadi pengangguran. Darmaningtyas pernah menegaskan bahwa pada mulanya ilmu pengetahuan dikembangkan bersama-sama oleh guru, siswa dan civitas akademika lainya melalui propses dialog tiada henti, baik itu lewat pengajaran, maupun penelitian. Tapi perjalanan selanjutnya, pengetahuan yang sejatinya menjadi orientasi bersama berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Dialog kritis lewat pengajaran dan penelitian kian hari kian ditinggalkan berganti dengan tembok pengetahuan yang seakan sudah mapan padahal itu hanya modifikasi pengetahuan.


Komentar